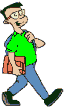LAPORAN PRAKTIKUM BIOTEKNOLOGI
PERTANIAN
“PRODUKSI PERTUMBUHAN Azolla sp TERHADAP TIGA JENIS MEDIA
(TANAH ULTISOL, TANAH GAMBUT DAN VERMIKOMPOS) DAN PENGOMPOSAN Azolla sp”
M. DENI
05071281419188
PROGRAM STUDI
AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS
SRIWIJAYA
2016
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Bioteknologi
adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang meng gunakan makhluk hidup untuk
menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung
dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel,
teknik kimia, dan enzimologi. Dalam bioteknologi biasanya digunakan
mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu
bahan
Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan
makhluk hidup (bakteri, fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk dari
makhluk hidup (enzim, alkohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.
Bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui
aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi
biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau
merekayasa gen pada organisme tersebut. Selain itu bioteknologi juga
memanfaatkan sel tumbuhan atau sel hewan yang dibiakkan sebagai bahan dasar
sebagai proses industri.
Prinsip-prisip bioteknologi telah digunakan untuk membuat
dan memodi-fikasi tanaman, hewan, dan produk makanan. Bioteknologi yang
menggunakan teknologi yang masih sederhana ini disebut bioteknologi
konvensional atau tradisional. Penerapan bioteknologi konvensional ini sering
diterapkan dalam pembuatan produk-produk makanan. Seiring dengan perkembangan
dan pe-nemuan dibidang molekuler maka teknologi yang digunakan dalam
bioteknologi pada saat ini semakin canggih.bioteknologi yang menggunakan
teknologi canggih ini disebut bioteknologi modern.
pengomposan (pengomposan tergolong
kedalam bioteknologi konvensional)
Pupuk Kompos sering didefinisikan sebagai suatu proses
penguraian yang terjadi secara biologis dari senyawa-senyawa organik yang
terjadi karena adanya kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu
didalam atau wadah tempat pengomposan berlangsung. Bahan pembuatan pupuk
organik atau lebih dikenal dengan kompos memanfatkan limbah pertanian, seperti
jerami, daun-daunan, rumput, pupuk kandang, serbuk gergaji, bahan tersebut
mudah didapat dan tersedia dilahan pertanian.
Proses pembuatan kompos disebut dengan pengomposan,
pengomposan merupakan salah satu cara pemanfaatan bioteknologi secara
konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan
mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. misalnya jamur
dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme
sehingga diperoleh produk yang diinginkan seperti kompos.
Tanah gambut merupakan tanah yang
berasal dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang sudah setengah membusuk sehingga
kaya akan berbagai macam unsur hara. Kebanyakan tanah yang satu ini terbentuk
di daerah yang berair, salah satunya adalah di Inggris. Lahan-lahan gambut yang
ada di dunia sendiri di kenal dengan berbagai macam nama mulai dari bog, moor,
muskeg dan yang lainnya. kandungan bahan organik yang cukup tinggi membuat
tanah gambut juga dikenal sebagai tanah untuk sumber energi, karena memang
berbagai macam tumbuhan bisa dengan mudah hidup pada tanah yang satu ini.
Tanah gambut sendiri bisa terbentuk
saat bagian-bagian dari tumbuhan baik itu akar, batang, daun dan yang lainnya
luruh dan membusuk, namun proses pembusukan tersebut terhambat oleh lingkungan
atau organisme yang lain sehingga hanya setengah jalan atau dikenal dengan
setengah membusuk. Tanah dikatakan sebagai tanah gambut jika kadar bahan
organik yang ada di dalamnya melebihi angka 30%, jumlah yang tentunya sangat
besar untuk sebuah tanah, tak heran jika berbagai macam tanaman bisa dengan
mudah tumbuh dan berkembang jika ditanam pada tanah ini.
Ultisol adalah tanah mineral yang berada pada daerah
temprate sampai tropika, mempunyai horison argilik atau kandik dengan lapisan
liat tebal. Dalam legend of soil yang disusun oleh FAO, ultisol mencakup
sebagian tanah Laterik serta sebagian besar Podsolik, terutama Podsolik Merah
Kuning (Mohr, baren dan borgh, 1972). Solum memiliki kedalamannya sedang
(moderat) 1 sampai 2 meter, warnanya merah sampai kuning, chroma meningkat
dengan bertambahnya kedalaman, tekstur halus pada horizon Bt (karena kandungan
liat maksimal pada horizon ini), struktur pada horizon Bt berbentuk blocky,
konsistensi yang teguh, permebilitasnya lambat sampai baik serta erodibilitas
yang tinggi.
Vermikompos adalah kompos yang diperoleh dari hasil perombakan
bahan-bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah. Vermikompos merupakan
campuran kotoran cacing tanah (casting) dengan sisa media atau pakan dalam budidaya cacing
tanah. Oleh karena itu, vermikompos merupakan pupuk organik yang ramah
lingkungan dan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kompos lain
yang kita kenal selama ini. Vermikompos
mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Penambahan kascing pada media tanam
akan mempercepat pertumbuhan, meningkatkan tinggi, dan berat tumbuhan. Jumlah
optimal kascing yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil positif hanya 10-20%
dari volume media tanaman
Azolla
sp adalah jenis tumbuhan paku air yang mengapung, banyak terdapat
diperairan yang menggenang terutama di sawah-sawah dan dikolam. Para petani
ikan mengenal dengan sebutan “ mata lele . Keistimewaan Azolla adalah dapat hidup bersimbosis dengan anabaena Azolla yang dapat memfiksasi Nitrogen
(N2) dari udara. Saat ini pemanfaatan Azolla
sudah mulai banyak digunakan mengingat ketersediaannya relatif banyak terdapat
pada areal pesawahan di Indonesia. Salah satunya adalah digunakan sebagai pupuk
organik pada bidang pertanian.
Azolla adalah
paku air mini yang berukuran 3-4 cm serta bersimbiosis dengan Cyanobacteria
pemfiksasi N2. Simbiosis ini menyebabkan Azolla mempunyai kualitas nutrisi yang baik. Azolla sudah berabad-abad digunakan di Cina dan Vietnam sebagai
sumber N bagi padi sawah. Azolla
tumbuh secara alami di Asia, Amerika, dan Eropa.Azolla mempunyai beberapa spesies, antara lain Azolla caroliniana, Azolla
filiculoides, Azolla mexicana, Azolla microphylla, Azolla nilotica, Azolla
pinnata var. pinnata, Azolla pinnata var. imbricata, dan Azolla rubra.
Tanaman
Azolla sp. memang sudah tidak
diragukan lagi konstribusinya dalam memengaruhi peningkatan tanaman padi. Hal
ini telah dibuktikan dibeberpa tempat dan beberapa negara. Konstribusi terbesar
Azolla adalah dengan dijadikan pupuk
organic atau kompos terbukti menjaga hasil panen tetap tinggi. Meskipun
penggunaannya sebagai pupuk hijau pada tanaman padi masih dilakukan di China
dan Vietnam, dengan adanya peningkatan biaya tenaga kerja, membuatnya kurang diminati.
Pemanfaatan
Azolla sebagai pupuk ini memang
memungkinkan. Pasalnya, bila dihitung dari berat keringnya dalam bentuk kompos
(Azolla kering) mengandung unsur
Nitrogen (N) 3-5%, Phosphor (P) 0,5 - 0,9% dan Kalium (K) 2- 4,5 %. Sedangkan
hara mikronya berupa Calsium (Ca) 0,4 - 1 %, Magnesium (Mg) 0,5 - 0,6 %, Ferum
(Fe) 0,06 - 0,26 % dan Mangaan (Mn) 0,11 - 0,16 %.
kompos Azolla sp merupakan pupuk organik yang memanfaatkan pembusukan bahan organik di dalam suatu tempat yang terlindung dari matahari dan hujan, dengan pengaturan kelembaban serta dilakukan
penyiraman air apabila kompos
terlalu kering. Untuk mempercepat perombakan di dalam kompos
maka dapat ditambah dengan
kapur, sehingga terbentuk
kompos dengan
C/N rasio yang rendah
dan siap digunakan sebagai pupuk organik.
Berdasarkan penjelasan
diatas maka penulis melakukan praktikum Bioteknologi Pertanian ini untuk
melihat perkembangan Azolla pada
berbagai jenis tanah atau media tanam, kemudian Azolla dijadikan kompos dari yang sudah di budidayakan pada jenis
media tanah yang berbeda untuk melihat respon pertumbuhan dan jumlah Azolla yang dihasilkan.
1.2.
Tujuan Praktikum
Adapun tujuan
dari praktikum ini adalah untuk membudidayakan Azolla serta untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan Azolla pada jenis tanah yang berbeda
yaitu tanah gambut, tanah ultisol dan vermikompos yang kemudian dijadikan
kompos.
1.3.
Manfaat Praktikum
Adapun manfaat dari
praktikum ini adalah untuk belajar bagamana cara membuat kompos Azolla sp serta cara budidayanya di kolam
buatan dengan media campuran beberapa jenis tanah.
BAB
2
TINJAUAN
PUSTAKA
2.1. Bioteknologi
Menurut Aryulina,dkk. (2004)
Bioteknologi berasal dari kata biologi dan teknologi.
Biologi adalah ilmu pengetahuan mengenai makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah
terapan ilmu pengetahuan dasar. Jadi, bioteknologi adalah suatu teknik yang
menggunakan makhluk hidup atau bahan yang diperoleh dari makhluk hidup dengan
tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.
Menurut Syamsuri,dkk. (2004)
Di dalam bioteknologi terdapat komponen-komponen sebagai
berikut:
1.
Bahan
yang diproses sebagai bahan masukan (input).
2.
Makhluk
hidup yang menyelenggarakan proses.
3.
Prinsip-prinsip
ilmu yang mendasari semua proses.
4.
Hasil
berupa produk atau jasa sebagai keluaran (output).
2.2. Kompos Dan Pengomposan
Kompos adalah bahan- bahan organik yang telah mengalami
proses pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme (bakteri
pembusuk) yang bekerja didalamnya. Bahan- bahan organik tersebut seperti dedaunan,
rumput, jerami, sisa-sisa ranting dan dahan, kotoran hewan dan lain-lain.
Penggunaan kompos dapat memberikan beberapa manfaat yaitu menyediakan unsur
hara makro dan mikro bagi tanaman, menggemburkan tanah, memperbaiki tekstur dan
struktur tanah, meningkatkan porositas, aerase dan komposisi mikroorganisme
tanah, memudahkan pertumbuhan akar tanaman, daya serap air yang lebih lama pada
tanah, menghemat pemakaian pupuk kimia, menjadi salah satu alternatif pengganti
pupuk kimia karena harganya lebih murah,
dan ramah lingkungan (Murbandono, 2000).
Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan-bahan
hijauan dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat
proses pembusukan, misalnya kotoran ternak atau bila dipandang perlu, bisa
ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea (Wied, 2004).
Proses pengomposan atau membuat kompos adalah proses biologis
karena selama proses tersebut berlangsung, sejumlah jasad hidup yang disebut
mikroba, seperti bakteri dan jamur, berperan aktif (Unus, 2002).
2.2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengomposan
a. Ukuran
Bahan
Bahan yang berukuran kecil akan cepat didekomposisi
karena luas permukaannya meningkat dan mempermudah aktivitas mikroorganisme
perombak. Ukuran bahan mentah yang terlalu kecil akan meyebabkan rongga udara
berkurang sehingga timbunan menjadi lebih mampat dan pasokan oksigen ke dalam timbunan
akan semakin berkurang. Jika pasokan oksigen berkurang, mikroorganisme yang ada
di dalamnya tidak bisa bekerja secara optimal (Djuarnani, dkk (2005).
b.
Nisbah C/N
Jika nisbah C/N tinggi,
aktivitas biologi mikroorganisme akan berkurang. Selain itu, diperlukan
beberapa siklus mikroorganisme untuk menyelesaikan degradasi bahan kompos
sehingga waktu pengomposan akan lebih lama dan kompos yang dihasilkan akan
memiliki mutu rendah. Jika nisbah C/N terlalu rendah (kurang dari 30),
kelebihan nitrogen (N) yang tidak dipakai oleh mikroorganisme tidak dapat
diasimilasi dan akan hilang melalui volatisasi sebagai amonia atau
terdenitrifikasi (Djuarnani dkk, 2005).
c.
Komposisi Bahan
Pengomposan dari
beberapa macam bahan akan lebih baik dan lebih cepat. Pengomposan bahan organik
dari tanaman akan lebih cepat bila ditambah dengan kotoran hewan. Ada juga yang
menambah bahan makanan dan zat pertumbuhan yang dibutuhkan mikroorganisme
sehingga selain dari bahan organik, mikroorganisme juga mendapatkan bahan
tersebut dari luar (Indriani, 2007).
Laju dekomposisi bahan
organik juga tergantung dari sifat bahan yang akan dikomposkan. Sifat bahan
tanaman tersebut diantaranya jenis tanaman, umur, dan komposisi kimia tanaman.
Semakin muda umur tanaman maka proses dekomposisi akan berlangsung lebih cepat.
Hal ini disebabkan kadar airnya masih tinggi, kadar nitrogennya tinggi,
imbangan C/N yang sempit serta kandungan lignin yang rendah (Simamora dan
Salundik, 2006).
d.
Kelembaban dan Aerasi
Bahan mentah yang baik
untuk penguraian atau perombakan berkadar air 50-70%. Bahan dari hijauan
biasanya tidak memerlukan tambahan air, sedangkan cabang tanaman yang kering
atau rumput-rumputan harus diberi air saat dilakukan penimbunan. Kelembaban
timbunan secara menyeluruh diusahakan sekitar 40- 60% (Musnamar, 2006). Aerasi
yang tidak seimbang akan menyebabkan timbunan berada dalam keadaan anaerob dan
akan menyebabkan bau busuk dari gas yang banyak mengandung belerang (Djuarnani
dkk, 2005).
e.
Temperatur
Pada pengomposan secara
aerobik akan terjadi kenaikan temperatur yang cukup cepat selama 3-5 hari
pertama dan temperatur kompos dapat mencapai 55- 700C. Kisaran temperatur
tersebut merupakan yang terbaik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Pada kisaran
temperatur ini, mikroorganisme dapat tumbuh tiga kali lipat dibandingkan dengan
temperatur yang kurang dari 550C. Selain itu, pada temperatur tersebut enzim
yang dihasilkan juga paling efektif menguraikan bahan organik. Penurunan nisbah
C/N juga dapat berjalan dengan sempurna (Djuarnani dkk, 2005).
f.
Keasaman (pH)
Keasaman
atau pH dalam tumpukan kompos juga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme.
Kisaran pH yang baik yaitu sekitar 6,5-7,5 (netral). Oleh karena itu,
dalam proses pengomposan sering diberi tambahan kapur atau abu dapur untuk
menaikkan pH (Indriani, 2007).
g. Pengadukan
atau Pembalikan
Tumpukan Pengadukan sangat diperlukan agar cepat
tercipta kelembapan yang dibutuhkan saat proses pengomposan berlangsung.
Pengadukan pun dapat menyebabkan terciptanya udara di bagian dalam timbunan,
terjadinya penguraian bahan organik yang mampat, dan proses penguraian
berlangsung merata. Hal ini terjadi karena lapisan pada bagian tengah tumpukan
akan terjadi pengomposan cepat. Pembalikan sebaiknya dilakukan dengan cara
pemindahan lapisan atas ke lapisan tengah, lapisan tengah ke lapisan bawah, dan
lapisan bawah ke lapisan atas (Musnamar, 2006).
h. Mikroorganisme
Dilihat dari fungsinya, mikroorganisme mesofilik
yang hidup pada temperatur rendah (10-450C) berfungsi untuk
memperkecil ukuran partikel bahan organik sehingga luas permukaan bahan
bertambah dan mempercepat proses. Sementara itu, bakteri termofilik yang hidup
pada temperatur tinggi (45-650C) yang tumbuh dalam waktu terbatas
berfungsi untuk mengonsumsi karbohidrat dan protein sehingga bahan kompos dapat
terdegradasi dengan cepat (Djuarnani dkk, 2005).
2.3. Azolla sp
Azolla sp adalah jenis tumbuhan paku air yang mengapung,
banyak terdapat diperairan yang menggenang terutama di sawah-sawah dan dikolam.
Para petani ikan mengenal dengan sebutan “mata lele”. Keistimewaan Azolla pinnata adalah dapat hidup
bersimbosis dengan anabaena Azolla
yang dapat memfiksasi Nitrogen (N2) dari udara. Saat ini pemanfaatan
Azolla pinnata sudah mulai banyak
digunakan mengingat ketersediaannya relatif banyak terdapat pada areal
pesawahan di Indonesia. Salah satunya adalah digunakan sebagai pupuk organik
pada bidang pertanian.
Istilah
Azolla berasal dari bahasa latin,
yaitu azo yang berarti kering dan ollyo yang berarti mati. Tumbuhan ini akan
mati apabila dalam keadaan kering. Azola merupakan tumbuhan jenis paku-pakuan
air yang hidupnya mengambang diatas permukaan air. Berukuran kecil, lunak,
bercabang-cabang tidak beraturan. Tumbuhan Azolla
pinnata merupakan tanaman air yang dapat ditemukan dari dataran rendah sampai
ketinggian 2200 m diatas permukaan laut. Azolla
banyak terdapat diperairan tenang seperti danau, kolam, rawa dan persawahan.
Selama ini tamanan Azolla dianggap
sebagai gulma air karena dalam waktu 3-4 hari dapat memperbanyak diri menjadi
dua kali lipat dari berat segarnya, sehingga dapat menutupi permukaan perairan
yang mengakibatkan mengurangi aktifitas fotosintesis mikroorganisme yang ada
didalam kolam (Handajani, 2007).
2.3.1.
Taksonomi
Menurut Sebayang (1996), Azolla sp merupakan tanaman paku-pakuan, termasuk
dalam famili Salviniaceae tetapi ada juga yang menamakan famili Azollaceae. Genus Azolla dikelompokkan menjadi dua, yaitu Euazolla
dan Rhizosperma. Secara
alami habitat Azolla
terdapat di kolam-kolam, tempat tergenang, danau, sungai, saluran air maupun tanaman padi. Azolla
berasal dari bahasa latin, yaitu Azo yang berarti kering dan Ollyo yang berarti mati. Tanaman ini akan mati bila dalam keadaan kering. Azolla termasuk
herba berukuran kecil yang hidup secara terapung bebas di air. Daun berukuran
kecil, tidak bertangkai,
Klasifikasi
Klasifikasi
Tumbuhan Azolla adalah sebagai berikut
:
Divisi
: Pteridophyta
Kelas : Leptosporangiopsida (heterosporous)
Ordo
: Salviniales
Famili
: Azollaceae
Genus
: Azollas
Spesies
: Azolla sp
2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Azolla
Kebutuhan utama Azolla untuk bertahan hidup adalah
habitat air, sehingga sangat sensitif terhadap kekeringan, jadi Azolla akan mati dalam beberapa jam jika
berada pada kondisi kering. Azolla
menyebar secara luas pada wilayah sedang, 11 umumnya sangat terpengaruh pada
tingginya temperatur, untuk hidup dengan baik, Azolla membutuhkan temperatur antara 20–25°C, sedang untuk dapat
bertumbuh dan berfiksasi nitrogen, Azolla
membutuhkan temperatur 20–30°C, Azolla
akan mati jika berada di bawah suhu 5°C dan di atas temperatur 45°C (Cecep,
2011). Azolla sering dimanfaatkan
sebagai pupuk organik dalam memproduksi padi di daerah tropis dataran rendah di
Asia Tenggara. Azolla mampu
bersimbiosis dengan Anabaena Azollae,
simbiosis ini mengakibatkan Azolla
dapat menambat nitrogen dari atmosfir, sehingga selanjutnya dapat digunakan
sebagai pupuk organik (Cecep, 2011).
Pada kondisi optimal Azolla akan tumbuh baik dengan laju pertumbuhan 35% tiap hari.
Nilai nutrisi Azolla mengandung kadar
protein tinggi antara 24-30% (Akrimi, 2001). Azolla
dapat tumbuh dengan baik pada temperatur rata-rata 15-30 OC. Temperatur optimum
kira-kira 25oC untuk Azolla
filiculoides, A rubra dan A japonica. Sedangkan emperature di bawah 10 OC
pertumbuhan Azolla kurang baik Azolla dapat beradaptasi di atas
emperature –5°C.
Sinar matahari sama halnya
dengan tumbuhan hijau lainnya, Azolla
juga butuh sinar matahari sebagai fotosintesis dan nitrogenase. Dimana Azolla yang tumbuh di daerah yang
kekurangan sinar matahari akan kurang baik pertumbuhannya. Sedangkan apabila
mendapat sinar matahari yang kuat juga kurang baik Azolla akan menjadi warna merah dan warna merah kecoklatan atau
mati. Sedangkan pada musim panas dan dingin Azolla
akan menjadi warna merah atau merah kecoklatan. Untuk menghindari hal tersebut
diatas kita harus menggunakan naungan agar tumbuhan Azolla dapat tumbuh dengan subur sehingga Azolla akan menjadi hijau. Azolla
dapat tumbuh dengan baik pada keadaan air atau tanah sedikit asam dengan pH 4.
Sedangkan pada kebutuhan mineral Azolla
dapat menyerap nutrisi dari air pada saat Azolla
mengapung di air. Sebab phospor yang ditebar dari tanah terurai secara
perlahan-lahan oleh air. Tapi populasi Azolla
yang mengapung di atas air kurang baik menyerap atau mengambil phospor
tersebut. Penerapan pupuk phospor akan lebih baik dan efektif untuk
meningkatkan pertumbuhan apabila di semprotkan di atas pertumbuhan Azolla. (Khan, 1988).
2.3.3. Pengembangbiakan
Azolla Sp
Menurut Khan (1988) Tempat
terbaik untuk budidaya adalah kolam tanah, bila tidak memakai kolam tanah,
tambahkan tanah dalam tempat itu (karena Azolla
suka media yg berlumpur), campurkan tanah dengan pupuk kandang (kotoran
kambing, kotoran ayam, atau yang lainnya) kedalam kolam, baik menggunakan kolam
terpal ataupun kolam tanah. Langkah selanjutnya, isi kolam dengan air minimal 5
cm (dari permukaan media pupuk) maksimal 20 cm, jangan terlalu tinggi air dalam
kolam akan lebih baik jika akar Azolla
dapat menjangkau media. dan yang tak kalah penting adalah sinar matahari,
semakin lama mendapat sinar matahari semakin baik. Media untuk budidaya Azolla dapat menggunakan bak plastik,
kolam, terpal, dan tempat lain yang tidak ada ikan berukuran besar, jika ada
ikan kecil (guppy,cere) tidak begitu bermasalah, justru bermanfaat agar tidak
menjadi perkembang biakan jentik nyamuk. Lakukan penyemprotan stok setiap tiga
bulan sekali menggunakan pupuk P (1 sendok makan SP-36 per 1 liter air).
Sebaiknya Sp-36 ditumbuk halus agar mudah larut dalam air. indukan ini
digunakan untuk bibit yang akan ditanam di lahan yang lebih besar.
Sebagai habitat asli
tanaman rawa atau sawah, budidaya Azolla
sp tidak sulit. Kunci utama mengembangkan tanaman ini adalah membuat media
tanam menyerupai habitat aslinya. Tanaman ini bisa dikembangkan di kolam terpal
yang diberi lumpur ataupun kolam tanah. Untuk menghasilkan
Azolla yang maksimal, baiknya tanah
yang akan dimasukkan dalam kolam dicampur dengan pupuk kandang kering.
Komposisi campurannya, 70% tanah dan 30% pupuk kandang. Selanjutnya, campuran
tanah dan pupuk kandang dimasukkan ke dalam kolam secara merata dengan
ketebalan sekitar 5 centimeter (cm). Setelah itu isi kolam dengan air
secukupnya. Setelah kolam siap baru dilakukan penebaran bibit. Saat penggunaan
pupuk kandang pada media, perhatikan bau air. apabila air menjadi bau, berarti
pupuk belum terfermentasi sempurna, jangan dipakai karena dapat membuat Azolla mati jika langsung ditanam.
Untuk kolam berukuran 2 x
3 meter, bisa diisi bibit sebanyak 1 kilogram. Biasanya bibit ini bersifat
basah, sehingga harus segera ditebar. Supaya Azolla bisa tumbuh maksimal, perhatikan ketinggian air di dalam
kolam. Ketinggian air di dalam kolam cukup antara 10 cm – 15 cm dari lumpur. Semakin
dekat jarak air dengan lumpur akan semakin baik karena akan mempercepat
perkembangan tanaman. Yang harus diperhatikan juga adalah posisi kolam.
Sebaiknya jangan tempatkan kolam di bawah sinar matahari langsung karena akan
merusak warna daun,warnanya bisa kecoklatan, sebaiknya diberi paranet. Namun
demikian, kolam juga tidak bisa dibuat di ruang tertutup karena Azolla membutuhkan nitrogen dan
berfotosintesis.tanaman ini dapat dipanen bila sudah memenuhi seluruh kolam
dengan membentuk tiga lapis tanaman. Setiap hari tanaman ini dapat tumbuh 30%
dari jumlah bibit yang disebar. Sehingga dalam waktu lima sampai tujuh hari Azolla sudah dapat dipanen. Untuk
memanen tanaman ini baiknya dalam satu kolam diambil secukupnya dan sesuai
kebutuhan. Tujuannya, agar petani tidak perlu membeli bibit baru dan tanaman
dapat terus berkembang. Untuk pemeliharaan, dapat menambah-kan pupuk kandang
kering atau pupuk kompos bila pertumbuhan Azolla
sudah kurang maksimal dan lambat.
2.3.4.
Kompos Azolla Sp
Kompos merupakan istilah untuk
pupuk organik buatan
manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup (tanaman maupun hewan) yang berperan dalam proses pertumbuhan tanaman, tidak hanya menambah
unsur hara tetapi juga menjaga
fungsi tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk kompos Azolla sp merupakan pupuk organik yang memanfaatkan pembusukan bahan organik di dalam suatu tempat yang terlindung dari matahari dan hujan, dengan pengaturan kelembaban serta dilakukan
penyiraman air apabila kompos
terlalu kering. Untuk mempercepat perombakan di dalam kompos
maka dapat ditambah dengan
kapur, sehingga terbentuk
kompos dengan
C/N rasio yang rendah
dan siap digunakan sebagai pupuk organik (Hardjowigeno, 1987)
2.4. Tanah Ultisol
Tanah Ultisol merupakan bagian terluas dari lahan
kering di Indonesia yaitu sekitar 51 juta ha (lebih kurang 29% luas daratan
Indonesia). Akhir-akhir ini menjadi sasaran utama perluasan lahan pertanian di
luar pulau Jawa dan menjadi sasaran bukaan lahan pemukiman transmigrasi. Oleh
karena itu, Ultisol perlu mendapat perhatian khusus mengingat kendala dan
sangat peka terhadap erosi (Munir, 1996).
Menurut Hardjowigeno (1993) bahwa
tanah Ultisol biasanya ditemukan di daerah-daerah dengan suhu rata-rata lebih
dari 8 ºC. Pembentukan tanah Ultisol banyak dipengaruhi oleh bahan induk tua
seperti batuan liat, iklim yang cukup panas dan basah, relief berombak sampai
berbukit. Tanah ini memiliki horizon Argilik yang bersifat masam dengan
kejenuhan basa yang rendah. Pada kedalaman 1,8 m dari permukaan tanah kejenuhan
basa kurang dari 35 %. Dari data analisis tanah ultisol dari berbagai wilayah
di Indonesia, menunjukkan bahwa tanah tersebut memiliki ciri reaksi tanah
sangat masam (pH 4,1 – 4,8). Kandungan bahan organik lapisan atas yang tipis
(8-12 cm), umumnya rendah sampai sedang. Kandungan N, P, K yang bervariasi
sangat rendah sampai rendah, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Jumlah
basa-basa tukar rendah, kandungan K-dd hanya berkisar 0 - 0,1 me/ 100 g disemua
lapisan termasuk rendah, dapat disimpulkan potensi kesuburan alami Ultisol
sangat rendah sampai rendah (Subagyo, dkk, 2000).
2.5. Tanah
Gambut
Lahan
gambut merupakan lahan yang berasal dari bentukan gambut beserta vegetasi yang
terdapat diatasnya, terbentuk di daerah yang topografinya rendah dan bercurah
hujan tinggi atau di daerah yang suhunya sangat rendah. Tanah gambut mempunyai
kandungan bahan organik yang tinggi (>12% karbon) dan kedalaman gambut
minimum 50 cm (Rina et al., 2008).
Secara umum definisi tanah gambut adalah tanah yang
jenuh air dan tersusun dari bahan tanah organik, yaitu sisa- sisa tanaman dan
jaringan tanaman yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Dalam sistem
klasifikasi baru (taksonomi tanah), tanah gambut disebut sebagai Histosols
(histos = jaringan) (Noor dan Heyde, 2007).
Menurut Agus dan Subiksa (2008), berdasarkan tingkat
kematangannya gambut dibedakan menjadi:
a. Gambut
saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan asalnya tidak
dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam, dan bila diremas kandungan seratnya
< 15%.
b. Gambut
hemik (setengah matang) adalah gambut setengah lapuk, sebagian bahan asalnya
masih bisa dikenali, berwarma coklat, dan bila diremas bahan seratnya 15 – 75%.
c. Gambut
fibrik (mentah) adalah gambut yang belum melapuk, bahan asalnyamasih bisa
dikenali, berwarna coklat, dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa.
Kesuburan tanah gambut dipengaruhi oleh kedalaman
dan lapisan mineral di bawah gambut. Makin tebal gambut makin miskin lapisan
atasnya. Gambut yang terbentuk di atas endapan pasir kuarsa lebih miskin dari
gambut yang terbentuk di atas endapan liat. Menurut Noor (2001), secara kimiawi
sifat tanah gambut yang utama adalah kemasaman tanah, ketersediaan hara tanah,
kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, kadar asam organik tanah, kadar pirit
atau sulfur. Sifat-sifat kimia tanah ini sangat penting dalam penentuan jenis
dan cara-cara pengelolaan hara dan pupuk dalam budidaya tanaman pertanian.
2.6. Vermikompos
Vermikompos adalah pupuk organik
yang diperoleh melalui proses yang melibatkan cacing tanah dalam proses
penguraian atau dekomposisi bahan organiknya. Walaupun sebagian besar
penguraian dilakukan oleh jasad renik, kehadiran cacing justru membantu memperlancar
proses dekomposisi. Karena bahan yang akan diurai jasad renik pengurai, telah
diurai lebih dulu oleh cacing. Proses pengomposan dengan melibatkan cacing
tanah tersebut dikenal dengan istilah vermikomposting. Sementara hasil akhirnya
disebut vermikompos (Agromedia, 2007 ).
Vermikompos adalah hasil dekomposisi
lebih lanjut dari pupuk kompos oleh cacing tanah yang mempunyai bentuk dan
kandungan hara lebih baik untuk tanaman (Hadiwiyono dan Dewi, 2000). Beberapa
keunggulan vermikompos adalah menyediakan hara N, P, K, Ca, Mg dalam jumlah
yang seimbang dan tersedia, meningkatkan kandungan bahan organik, meningkatkan
kemampuan tanah mengikat lengas, menyediakan hormon pertumbuhan tanaman,
menekan resiko akibat infeksi patogen, sinergis dengan organisme lain yang
menguntungkan tanaman serta sebagai penyangga pengaruh negatif tanah (Sutanto,
2002).
Vermikompos mengandung nutrisi yang
dibutuhkan tanaman. Penambahan kascing pada media tanam akan mempercepat
pertumbuhan, meningkatkan tinggi, dan berat tumbuhan. Jumlah optimal kascing
yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil positif hanya 10-20% dari volume media
tanaman (Mashur, 2001).
BAB 3
PELAKSANAAN PRAKTIKUM
3.1. Waktu dan Tempat
Adapun
waktu pelaksanaan praktikum bioteknologi pertanian ini dilaksanakan mulai tanggal
Adapun
tempat pelaksanaan praktikum bioteknologi pertanian ini dilakukan di samping
Rumah Kaca Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya,
Inderalaya.
3.2. Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan pada praktikum
bioteknologi pertanian antara lain sebagai berikut: 1) Alat Tulis 2)
Cangkul 3) Kayu 4) Parang 5) Terpal 6)
Ember
Adapun bahan yang digunakan pada
praktikum bioteknologi pertanian antara lain sebagai berikut: 1) Air 2) Bibit Azolla sp. 3) Pupuk 4) Tanah Gambut 6)
Tanah Ultisol 5) Vermikompos 6)
3.3. Cara Kerja
Adapun cara kerja dari praktikum ini antara lain
sebagai berikut:
1. budidaya Azolla sp
2. pengomposan Azolla sp