
Logo Himagrotek Unsri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPORAN
TETAP
PRAKTIKUM PESTISIDA
DAN APLIKASINYA
“UJI TOKSISITAS RESIDU
INSEKTISIDA BERBAHAN AKTIF DIMEHYPO PADA TANAMAN KUBIS (Brassica oleracea) TERHADAP
SERANGGA JANGKRIK
(Gryllus asimilis)”

M. DENI
05071281419188
PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS
SRIWIJAYA
INDERALAYA
2016
BAB
1
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pangan merupakan
kebutuhan dasar manusia (UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan). Setiap orang
berhak mendapatkan pangan yang mengandung zat gizi dan aman dari segala
kontaminan yang merugikan (UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Kemungkinan
pangan untuk terkontaminasi semakin tinggi, sebagai akibat dari suatu penerapan
teknologi (Slamet, 1994). Teknologi pertanian ditujukan untuk mengatasi masalah
yang muncul pada pertanian, yaitu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (Suprapti,
2011). Dalam perspektif kesehatan, penerapan teknologi adalah suatu risiko bagi
kesehatan (Achmadi, 2008).
Sayuran dalam kehidupan manusia sangat berperanan dalam pemenuhan kebutuhan
pangan dan peningkaan gizi, karena sayuran merupakan salah satu sumber mineral
dan vitamin yang dibutuhkan manusia.
Konsumsi sayuran oleh masyarakat saat ini masih dibawah kebutuhan gizi yang
seharusnya. Konsumsi sayuran oleh rakyat Indonesia masih sekitar 61 % dari
kebutuhan yang seharusnya. Pada tahun 1978 telah ditetapkan bahwa untuk
memenuhi gizi rata-rata orang Indonesia memerlukan 65,7 kg sayuran dalam satu
tahun.
Konsumsi sayuran yang masih rendah
tersebut disebabkan banyak hal antara lain tingkat pengetahuan rata-rata
masyarakat yang masih rendah dan produktvitas sayuran yang rendah.
Faktor-faktor pembatas produktivitas yang penting adalah adanya serangan berbagai
jeis hama tanaman dan masalah penanganan pasca panen yang dapat menurunkan
kuantias dan kualitas sayuran. Salah atu usaha agar produktivitas sayuran dapat
ditingkatkan diperlukan tindakan pengendalian hama dan penanganan pasca panen
yang efektif dan efisien.
Risiko bagi kesehatan masyarakat adalah adanya residu insektisida dalam
makanan (Lu, 1995). Berbagai penelitian
pada bahan pangan di beberapa wilayah di Indonesia, menunjukan bahwa pada
makanan terbukti adanya residu beberapa insektisida, bahkan berbagai temuan
Kubis merupakan sayuran daun utama di dataran tinggi bahkan merupakan salah
satu sayuran prioritas di Indonesia (Adiyoga dkk, 2008). Menurut data BPS
(2010), jenis komoditi hasil pertanian yang paling dominan diproduksi di
Indonesia tahun 2010 adalah sayuran kubis (1,384,044ton). Dalam pemanfaatannya,
kubis dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan (Permentan
No.88 Tahun 2011).
Kadar residu
insektisida dapat menurun oleh karena proses pengolahan makanan. Hal ini
diakibatkan oleh karena proses hidrolisis, penguapan, dan degradasi zat kimia
(Soemirat, 2009). Proses pencucian adalah hal yang umum dilakukan di rumah
tangga karena dapat dilakukan dengan baik air maupun larutan pencuci yang
tersedia di dapur. Bahan kimia alami yang direkomendasikan untuk tujuan
penurunan residu pestisida adalah garam (NaCl), natrium bikarbonat (NaHCO3),
dan asam cuka (CH3COOH) (Klinhom, 2008).
Residu insektisida masih dapat tertinggal pada sayuran yang diperlakukan
dengan insektisida. Residu insektisida diketahui dapat menyebabkan gangguan
kesehatan (keracunan) baik akut maupun kronik. Upaya penurunan kadar residu
perlu dilakukan agar pangan aman dikonsumsi.
Oleh karena penggunaan pestisida yang intensif di lapangan, residu
pestisida dalam sayuran, terutama sayuran yang biasa dikonsumsi dalam bentuk
bahan mentah, merupakan masalah sayuran yang perlu diperhatikan dalam
hubungannya dengan kualitas dan keamanan sayuran terhadap kesehatan masyarakat.
Untuk meneliti permasalahan tersebut perlu dilakukan
analisis sejak dari perlakuan pestisida di lapangan sampai pada cara pengolahan
sayuran.
1.2.
Tujuan
Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk menguji toksisitas residu insektisida berbahan aktif Dimehypo pada
tanaman Kubis (Brassica oleracea) terhadap serangga Jangkrik (Gryllus asimilis).
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kubis
Kol atau kubis merupakan tanaman sayur famili Brassicaceae berupa
tumbuhan berbatang lunak yang dikenal sejak jaman purbakala (2500-2000 SM) dan
merupakan tanaman yang dipuja dan dimuliakan masyarakat Yunani Kuno. Kubis atau
kol dengan nama latin (Brassica Oleracea Var Capitata) pada mulanya
merupakan tumbuhan liar di daerah subtropik. Tanaman ini berasal dari daerah
Eropa yang ditemukan pertama di Cyprus, Italia dan Mediteranian. Tanaman kubis
termasuk dalam golongan tanaman sayuran semusim atau umur pendek. Tanaman kubis
hanya dapat berproduksi satu kali setelah itu akan mati. Pemanenan kubis dilakukan
pada saat umur kubis mencapai 60 – 70 hari setelah tanam (Cahyono, 2001).
Kubis memiliki ciri
khas membentuk krop. Pertumbuhan awal ditandai dengan pembentukan daun secara
normal. Namun semakin dewasa daun-daunnya mulai melengkung ke atas hingga akhirnya
tumbuh sangat rapat. Pada kondisi ini petani biasanya menutup krop dengan
daun-daun di bawahnya supaya warna krop makin pucat. Apabila ukuran krop telah
mencukupi maka kubis siap dipanen. Kubis segar mengandung banyak vitamin,
seperti vitamin A B, C dan E. tingginya kandungan vitamin C pada kubis dapat
mencegah timbulnya sariawan. Vitamin-vitamin ini sangat berperan dalam memenuhi
kebutuhan manusia. Mineral yang banyak dikandung adalah kalium, kalsium,
fosfor, natrium, dan besi. Kubis segar juga mengandung sejumlah senyawa yang
merangsang pembentukan glutation, zat yang diperlukan untuk menonaktifkan zat
beracun dalam tubuh manusia.
Adapun gambar tananam kubis dapat dilihat pada
berikut
Kubis adalah salah satu sayuran dari keluarga cruciferae (brassicaceae)
yang dapat menjadi pilihan makanan yang baik karena memberikan serat dan
vitamin dasar namun rendah kalori. Sayuran ini lazim ditanam di Indonesia
seperti keluarga cruciferae yang lain seperti kubis bunga, kubis tunas,
brokoli, sawi, dll. Sayuran ini dapat ditanam di dataran rendah maupun di
dataran tinggi dengan curah hujan rata-rata 850-900 mm. Daunnya bulat, oval,
sampai lonjong, membentuk roset akar yang besar dan tebal, warna daun
bermacam-macam, antara lain putih (forma alba), hijau, dan merah
keunguan (forma rubra). Buahnya buah polong berbentuk silindris, panjang
5-10 cm, berbiji banyak. Biji berdiameter 2-4 mm, berwarna cokelat kelabu.
Kubis mempunyai nama
daerah kol, kobis, kubis telur, kubis krop dan nama asingnya yaitu cabbage.
Sedangkan nama simplisia dari kubis adalah Brassicae capitatae folium (daun
kubis) karena yang dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daunnya. Umur
panennya berbeda-beda, berkisar dari 90 hari sampai 150 hari. Kubis dapat
diperbanyak dengan biji atau setek tunas.
2.2. Jangkrik
Jangkrik merupakan serangga atau
insekta berukuran kecil sampai besar yang berkerabat dekat dengan belalang dan
kecoa karena diklasifikasikan ke dalam ordo Orthoptera. Jangkrik juga
merupakan hewan yang aktif pada malam hari dan berdarah dingin. Klasifikasi
jangkrik adalah filum Arthopoda, kelas Hexapoda (Insecta),
ordo Orthoptera, sub ordo Ensifera, famili Gryllidae (Jangkrik),
sub famili Gryllinae(Jangkrik lapang/rumah), genus Gryllus,
spesies Gryllus bimaculatus (Jangkrik Kalung), Gryllus mitratus (Jangkrik
Cliring) dan Gryllus testaceus (Jangkrik Cendawang). Morfologi tubuh
jangkrik Kalung sama dengan jangkrik-jangkrik pada umumnya yaitu terdiri atas
tiga bagian utama kepala, toraks (dada) dan abdomen (perut) serta setiap spesies
jangkrik memiliki ukuran dan warna yang beragam (Borror et al., 1992).
Jangkrik termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Siklus hidupnya dimulai dari telur kemudian menjadi jangkrik muda (nimfa)
dan melewati beberapa kali stadium instar terlebih dahulu sebelum menjadi
jangkrik dewasa (imago) yang ditandai dengan terbentuknya dua pasang
sayap (Borror et al., 1992).
2.3 Insektisida
Salah satu jenis dari pestisida adalah insektisida.
Insektisida merupakan bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk
membunuh serangga. Insektisida dapat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan,
tingkah laku, perkembangbiakan, kesehatan, sistem hormon, sistem pencernaan,
serta aktivitas biologis lainnya hingga berujung pada kematian serangga
pengganggu tanaman Insektisida termasuk salah satu jenis pestisida. Insektisida
dapat dibedakan menjadi golongan organik dan anorganik. Insekstisida organik mengandung
unsur karbon sedangkan insektisida anorganik tidak. Insektisida organik umumnya
bersifat alami, yaitu diperoleh dari makhluk hidup sehingga disebut insektisida
hayati.
Insektisida yang paling banyak beredar di pasaran merupakan insektisida
yang berada pada golongan organofosfat. Organofosfat merupakan insektisida yang
paling toksik diantara jenis pestisida lainnya. Organofosfat dapat terurai
dilingkungan dalam jangka waktu ± 2 minggu. Insektisida yang termasuk ke dalam
golongan organofosfat adalah diazinon, dimetoat, fenitrotin, klorpirifos, dan
profenofos. Insektisida jenis organofosfat mempunyai toksisitas sedang terhadap
mamalia, tetapi dapat meracuni pemakainya melalui mulut, kulit ataupun
pernafasan (Yusniati, 2008).
Senyawa organofosfat tidak stabil karena mudah terurai
pada permukaan tanah melalui proses dekomposisi dengan produk akhir yang
dihasilkan berupa karbon dioksida, dan air (Irie, 2007). Senyawa golongan
organofosfat menghambat enzim asetilkolin esterase yang berfungsi menghidrolisis
asetilkolin pada sinapsis sistem syaraf. Keracunan akibat senyawa golongan
organofosfat akan menyebabkan otot-otot menjadi kejang dang penderita akan
mengelepar – gelepar serta pusing, gemetar dan penglihatan menjadi kabur.
Golongan organofofosfat yang banyak beredar di pasaran selain klorpirifos
adalah profenofos (Yusniati, 2008).
2.4 Residu Pestisida Pada Sayur
Residu pestisida adalah
sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam
jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah. Selain itu, residu
pestisida juga diartikan sebagai sisa pestisida yang ditinggalkan sesudah
perlakuan dalam jangka waktu yang telah menyebabkan terjadinya
peristiwa-peristiwa khemis dan fisis mulai bekerja. Residu pestisida dapat
hilang atau terurai dengan cepat (disipasi) atau lambat (persistensi). Residu
pestisida pada tanaman dapat berasal dari hasil penyemprotan pada tanaman.
Residu pestisida terdapat pada semua tubuh tanaman seperti batang, daun, buah,
dan juga akar. Khusus pada buah, residu ini terdapat pada permukaan maupun
daging dari buah tersebut. Walaupun sudah dicuci atau dimasak, residu pestisida
ini masih terdapat pada bahan makanan (Zulkarnain, 2010).
Penggunaan
pestisida khususnya pada tanaman akan meninggalkan residu pada produk
pertanian. Bahkan pestisida tertentu masih dapat ditemukan sampai saat produk
pertanian tersebut diproses untuk pemanfaatan selanjutnya maupun dikonsumsi.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Munarso, dkk. (2009) di Malang dan Cianjur
ditemukan residu pestisida pada kubis, tomat, dan wortel. Hasil analisis
menemukan sebanyak 0,374 mg/kg endosulfan pada kubis, 0,106 mg/kg endosulfan
pada wortel, dan 0,079 mg/kg profenofos pada tomat. Selain itu ditemukan residu
pestisida pada sayuran kacang panjang dengan total 0.0129 mg/kg, serta
penelitian yang dilakukan oleh Elvira, dkk (2013) di Pasar Pannampu dan Lotte
Mart Kota Makasar terdapat kandungan residu insektisida berbahan aktif
profenofos pada sayuran sawi sebesar 0,0197 mg/kg.
BAB III
PELAKSANAAN
PRAKTIKUM
3.1. Waktu dan Tempat
Adapun Praktikum
Pestisida dan Aplikasinya ini dilakukan pada hari Kamis, April 2016, Pukul 11.30 WIB s-d selesai yag
bertempat di Ruang Insectarium, Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas
Pertanian Universitas Sriwijaya, Inderalaya.
3.2.
Alat dan Bahan
Adapun alat yang
digunakan pada praktikum kali ini yaitu : 1). Botol selai 2). Plastik 3).
Kertas 4). Karet 5). Gelas ukur 6).
Pipet tetes 7). Kamera 8). Alat tulis 9). Aplikasi SPSS. Adapun bahan yang digunakan
yaitu : 1). Kubis 2). Jangkrik 3). Insektisida berbahan aktif Dimehypho 4).
Air.
3.3.
Cara Kerja
Adapun cara kerja dari
praktikum ini adalah:
1. Siapakan
Jangkrik dan Kubis.
2. Siapkan
botol selai.
3. Masukan
jangkrik kedalam botol selai.
4. Buat
perlakuan terhadap kubis, dengan perlakuan tanpa dicuci, dicuci, dan di beri
Insektisida Dimehypo.
5. Kemudian
masukan masing-masing kubis kedalam botol selai, lalu botol ditutup.
6. Amati
jangkrik yang mati pada beberapa perlakuan tersebut.
7. Catat
jangkrik yang mati, kemudian lakukan perhitungan probit dengan Aplikasi SPSS.
BAB IV
HASIL DAN
PEMBAHASAN
4.1. Hasil
Tanggal
|
Perlakuan
|
Ulangan
|
Jumlah jangkrik yang
mati
|
Jumlah jangkrik yang
hidup
|
Jum’at, 16 April 2016
|
1
|
1
|
0
|
10
|
2
|
3
|
7
|
||
2
|
1
|
1
|
9
|
|
2
|
0
|
10
|
||
3
|
1
|
2
|
8
|
|
2
|
2
|
8
|
||
4
|
1
|
10
|
0
|
|
2
|
0
|
10
|
|
Tabel 1. Respon Jangkring terhadap tiap perlakuan
|
Keterangan :
Perlakuan 1 = Kubis langsung tanpa
pestisida dan tanpa dicuci
Perlakuan 2 = Kubis dicuci dengan
air
Perlakuan 3 = Kubis + Insektisida
Perlakuan 4 = Tidak diberi kubis (diberi
makanan berupa daun kering yang berasal dari tempat penjual
|
Tabel 1.2; LD 50 Perlakuan Kontrol |
|
Tabel 1.3 LD 50 perlakuan dicuci
|
|
Tabel 1.3 Perlakuan Insektisida
|
|
Tabel 1.4 Perlakuan tanpa Kubis
|
4.1 Pembahasan
Residu pestisida adalah
pestisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman
pertanian. Tingkat residu pada bahan pangan umumnya diawasi dan ditetapkan
batas amannya oleh lembaga yang berwenang di berbagai negara. Paparan populasi secara
umum dari residu ini lebih sering terjadi melalui konsumsi bahan pangan yang
ditanam dengan perlakuan pestisida, ditanam atau diproses di tempat yang dekat
dengan area berpestisida. Banyak dari residu pestisida ini merupakan pestisida
sintetik berbahan dasar klor yang menunjukan sifat bioakumulasi yang dapat
terkumpul dan menumpuk di dalam tubuh dan lingkungan hingga pada jumlah yang
membahayakan. Senyawa kimiawi yang persisten dapat terakumulasi di dalam rantai
makanan tanpa terurai, dan telah terdeteksi di berbagai produk hewan mulai dari
daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan daging ikan.
Insektisida yang diaplikasikan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada
tanaman kubis bersifat persisten atau sukar terurai, hal ini menyebabkan bahan
aktif yang ada didalam insektisida tersebut meninggalkan residu bahan aktif
pada tanaman kubis yang menempel pada permukaan tanaman kubis itu sendiri.
Seperti yang dijelaskan oleh Arnoldi (2012) bahwa, residu
insektisida masih dapat tertinggal pada sayuran yang diperlakukan dengan
insektisida. Residu insektisida diketahui dapat menyebabkan gangguan kesehatan
(keracunan) baik akut maupun kronik. Upaya penurunan kadar residu perlu
dilakukan agar pangan aman dikonsumsi. Hal ini tentunya akan membahayakan konsumen yang mengkonsumsi kubis
terlebih lagi yang tidak lagi dicuci.Hal ini dapat dilihat dari hasil
penelitian kubis yang tidak diberikan perlakuan apapun, kandungan bahan
aktifnya masih tinggi. LD 50 dari kubis yang dicuci lebih tinggi daripada kubis
yang tidak lagi dicuci, hal ini menunjukkan bahwa kandungan bahan aktif kubis
yang dicuci mengurangi residu insektisida yang ada dikubis yang mana
ditunjukkan oleh LD yang didapat dari hasil perhitungan probit menggunakan
software SPSS.
Tingginya tingkat penggunaan Insektisida oleh petani Indonesia membuat
kubis-kubis yang beredar dipasaran membuat kubis-kubis tersebut perlu perhatian
dan perlakuan lebih untuk membersihkan residu insektisida yang tertinggal dan
mengendap dikubis yang ada dipasaran. Hal ini disampaikan oleh Agung (2008)
bahwa, adapun
untuk mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kubis seperti;
Ulat Tritip (Plutellaxylostella), Ulat Titik Tumbuh (Crocidolomia binotalis
Zell), Ulat Grayak (Prodenia litura F), Kutu Daun (Myzus persicae Sulz), dan
penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri seperti penyakit rebah
batang yang disebabkan oleh cendawan Pythium debaryanum, dan penyakit busuk
hitam yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonascampestris, petani mengunakan
pestisida seperti, Curacron 500 EC, Decis 2,5 EC, Dursban 200 EC, Sevin 85 WP
Dharmasan 600 EC Diazinon 60 EC dan Dharmabas 500 EC. Pengendalian yang
dilakukan oleh petani terhadap hama dan penyakit diatas sangat tergantung dari
kondisi tanaman di lapangan, tapi secara umum rata-rata petani melakukan
penyemprotan sejak tanam sampai panen antara 4 - 6 kali (85%) sesuai dosis dan
konsentrasi anjuran dalam kemasan insektisida. Sedangkan penanganan pascapanen
dilakukan hanya dengan menghilangkan helaian daun paling luar yang terkena serangan
hama penyakit atau yang sudah tua/robek dan kotor karena tanah pada saat panen
dan tidak dilakukan pencucian (100%). Krop Kubis atau Kol dari lahan pertanian
langsung dibawa ke pasar tujuan, hasil survei di tingkat pedagang juga
menunjukkan tidak dilakukan pencucian terhadap krop kubis yang dijual (100%).
Yang lebih mengejutkan bahwa LD 50 dari kubis yang tidak diperlakukan
apa-apa lebih tinggi ketimbang kubis yang diberi perlakuan tambahan
insektisida, hal tersebut menunjukkan bahwa insektisida yang diaplikasikan oleh
petani melebihi dosis yang seharusnya untuk pengaplikasian insektisida. Hal ini
sangat memprihatikan karena hal ini akan merusak lingkungan sekitar perkebunan
akibat dari penggunaan insektisida yang tidak bijak dan akan memberikan dampak
buruk bagi konsumen yang kurang teliti didalam mengkonsumsi kubis yang memiliki
banyak residu insektisida yang ada didalamnya.
BAB V
KESIMPULAN
DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Adapun
kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah:
1. Pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pangan
yang mengandung zat gizi dan aman dari segala kontaminan yang merugikan.
2. Konsumsi sayuran masih rendah yang
disebabkan banyak hal antara lain tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang
masih rendah dan produktvitas sayuran yang rendah.
3. Kol
atau kubis merupakan tanaman sayur famili Brassicaceae berupa tumbuhan
berbatang lunak yang dikenal sejak jaman purbakala (2500-2000 SM) dan merupakan
tanaman yang dipuja dan dimuliakan masyarakat Yunani Kuno.
4. Penggunaan pestisida khususnya pada
tanaman akan meninggalkan residu pada produk pertanian. Bahkan pestisida
tertentu masih dapat ditemukan sampai saat produk pertanian tersebut diproses
untuk pemanfaatan selanjutnya maupun dikonsumsi.
5. Residu
pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada
atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
6.1. Saran
Adapun
saran yang dapat disampaikan dari praktikum ini adalah agar kita lebih berhati-hati
dalam mengkonsumsi sayuran yang ada dipasaran, terutama kubis karena masih
terdapat residu pestisida yang digunakan untuk mengendali-kan ham dan penyakit
tanaman tersebut, dan sebaiknya sayuran tersebut dicuci terlebih dahulu sebelum
dimasak dan dikonsumsi.
DAFTAR
PUSTAKA
Achmadi, U.F., 2008. Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. Jakarta: UI Press.
Adiyoga,
W. 2008. Pola Pertumbuhan Produksi
Beberapa Jenis Sayuran di Indonesia. Jurnal Hortikultura 9(2): 258-265.
Alen, Y., Zulhidayati. 2015. Pemeriksaan
Residu Pestisida Profenofos pada Selada (Lactuca sativa L.) dengan Metode
Kromatografi Gas. Jurnal Sains
Farmasi & Klinis, 1(2), 140-149.
Azis, Thamrin.
2011. Analisis Residu Pestisida Diazinon
Dalam Tanaman Kubis (Brassica Olarecea) Menggunakan Biosensor Elektrokimia
Secara Voltametri Siklik. J. Prog. Kim. Si. 2011, 1 (1) 32-40 32
Borror. 1992. Pengenalan
Pelajaran Serangga, edisi VI. Yogyakarta : Gajah Mada
Press
Cahyono, B. (2001). Kubis Bunga dan
Broccoli. Kanisius, Yogyakarta. Halaman. 12-14.
Elvira,
dkk., 2013. Identifikasi Residu Pestisida
Malathion Dalam Sayuran Sawi (Brassica juncea L.) di Pasar Pannampu dan Lotte
Mart Kota Makassar. Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Unhas Makassar.
Frank, C. Lu.,
1995, Toksikologi Dasar Asas, Organ Sasaran, dan Penilaian Resiko. Edisi
II, Penerjemah Edi Nugroho, 358, UI-Press, Jakarta.
Hartini, E., Supriyono, 2013. Laporan Akhir Dosen Pemula.
Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
Irie,
M., 2007, Pestiside residues in food, report of the JMPR 2007, FAO plant production and protection paper,
191, pp 210 pages 1357.
Klinhom P,
Markvichitr K, Vijchulata P, Tumwasorn S, Bunchasak C, Choothesa A. 2008.
Effect Of Restricted Feeding On Metabolic Adaptations Of Kamphaengsaen And
Crossbred Brahman Heifers. Animal Science Journal 77: 399-406.
Maruli,Arnold. Dkk., 2012. Analisa
Kadar Residu Insektisida Golongan Organofosfat Pada Kubis (Brassica oleracea)
Setelah Pencucian Dan Pemasakan Di Desa Dolat Rakyat Kabupaten Karo Tahun 2012.
Departemen Kesehatan Lingkungan
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Munarso,
Joni, dkk. 2009. Studi Kandungan Residu Pestisida pada Kubis, Tomat dan
wortel Di Malang dan Cianjur. Buletin Tekhnologi Pascapanen Pertanian, Vol
5 (31) (online). http://www.litbangpascapanenpertanian. co.id (Akses
28-04-2016).
Munarso, S.Joni. Miskiyah, Dan Broto, Wisnu. 2009. Studi Kandungan Residu Pestisida Pada Kubis,
Tomat, Dan Wortel Di Malang Dan Cianjur. Balai Besar Penelitian Dan
Pengembangan Pascapanen Pertanian.
Permentan
No.88 Tahun 2011. Tentang Pengawasan
Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
Pratiwi, Yuli. 2015. Analysis
Of Pesticide Thiametoxam Pesticide Residu Cabbage In Vegetables (Brassica
oleracea var. capitata L). Pharmaconjurnal Ilmiah Farmasi – Unsrat Vol. 4
No. 1 Februari 2015 Issn 2302 - 2493
Sitambul, R. 2014.
Analisis Residu Pestisida Klorpirifos
Pada Sawi Hijau (Brassica rapa var.parachinensis L.) Asal Desa Kanreapia
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa Secara Kromatografi Gas. Program
Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar.
Soemirat,
Juli. 2009. Epidemiologi Lingkungan.
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Sudewa,
A. K., Residu Pestisida Pada Sayuran
Kubis (Brassica oleracea L.),
Ecotrophic ♦ 4 (2) : 125‐130.
Suprapti.
W. (2010). Perilaku Konsumen Pemahaman Dasar Dan Aplikasinya Dalam Strategi
Pemasaran. Bali : Udayana University Press.
Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
Yuliastuti, Sri. Teknik Analisis Pestisida Organoklorin Pada
Tanaman Kubis Dengan Menggunakan Kromatografi Gas. Buletin Teknik Pertanian
Vol. 16, No. 2, 2011: 74-76.
Yusnani, Anwar, D., 2013. Identifikasi Residu Pestisida Golongan
Organofosfat Pada Sayuran Kentang Di Swalayan Lottemart Dan Pasar Terong Kota
Makassar Tahun 2013. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Dan
Pengendalian Penyakit, Makassar.
Yusniati, 2008. Pengendalian
Hama Terpadu Pada Padi Sawah. Diakses pada 28 April 2016, www.sdsindonesia.com.
Zulkarnain,
2010. Dasar-Dasar Hortikultura. PT Bumi Aksara, Jakarta.





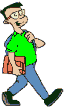
Wew
ReplyDeleteHahahha Sering sering mampir :D
Delete